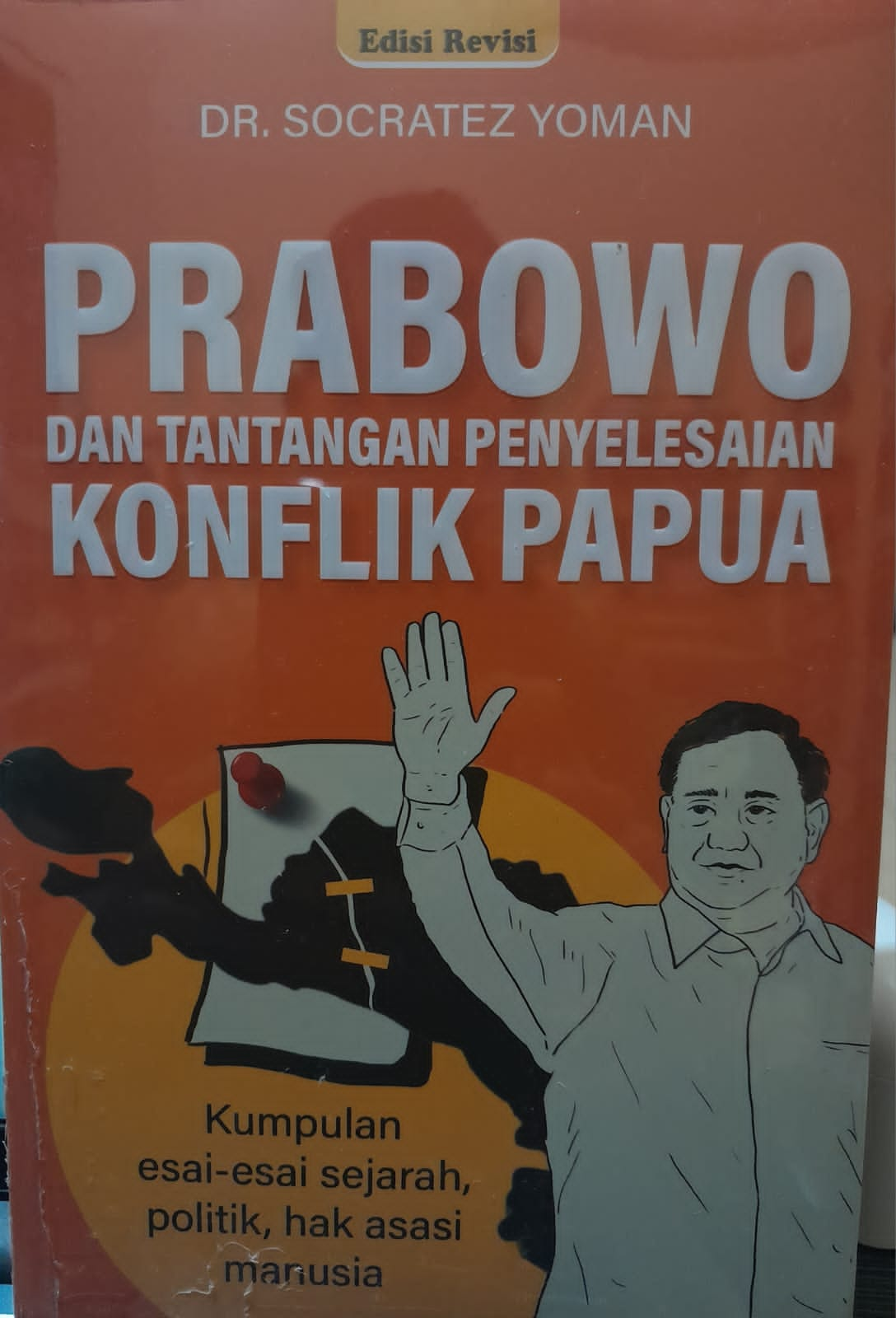oleh: Dr. Socratez Yoman
Rasisme dan ketidakadilan sebagai jantung persoalan Papua bertumbuh subur dan berurat akar di Papua sejak 1969 sampai dengan era Otonomi Khusus 2001 hingga kini. Ada beberapa fakta rasisme dan ketidakadilan yang menjadi catatan penting penulis.
Kasus Tolikara, Jumat, 17 Juli 2015, sebanyak 11 orang ditembak aparat keamanan Indonesia dan 10 orang luka luka. Rasisme dan ketidakadilan terlihat ketika Panglima TNI, Kapolri, Menteri Sosial datang ke kabupaten Tolikara hanya mengurus orang-orang pendatang di Tolikara, urus kayu-kayu, dan seng kios yang terbakar. Kios itu digunakan sebagai tempat ibadah (Musola). Musola itu terbakar, bukan dibakar. Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Sosial tidak mempersoalkan 10 orang yang luka-luka akibat ditembak aparat keamanan Indonesia dan 1 orang bernama Endi Wanimbo yang tewas.
Kasus rasisme yang meletus lebih besar dan hebat terjadi pada 2019. Rasisme yang terjadi di Surabaya itu dilawan dengan aksi damai dengan skala besar di berbagai daerah di Papua dan daerah lain di luar Papua pada 19 Agustus-23 September 2019. Demo damai melawan rasisme dipicu dari peristiwa rasisme yang terjadi pada 15-17 Agustus 2019 di Semarang, Malang, dan Yogyakarta yang dilakukan oleh organisasi massa radikal seperti Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila (PP), anggota TNI, dan Forum Komunikasi Putra Putri Purna wirawan TNI (FKPP).
Aksi melawan rasisme itu kemudian menyulut konflik lain yang berakibat pada jatuhnya korban di kalangan orang asli Papua, antara lain:
- Marselino Samon (15) pelajar SMA ditikam hingga tewas pada 29 Agustus 2019 di belakang Kantor Pos Jayapura.
- Evert Mofu (21) penjaga gudang kontainer pada 29 Agustus 2019 dibacok kepala dan mati di tempat di Telkom Kota Jayapura.
- Maikel Kareth (21) mahasiswa Uncen semester 7 pada 31 Agustus 2019 ditembak didada tembus belakang dengan peluru tajam.
- Oktovianus Mote (21) Mahasiswa STIKOM Muhammadiyah pada 30 Agustus 2019 jenazah disimpan di freezer di RS Bhayangkara dan jenazah diambil keluarga pada 25 September 2019.
Semua korban tewas ini dari tangan milisi, Barisan Merah Putih, dan Paguyuban Nusantara. Aksi kriminal dari kelompok tersebut bergerak leluasa tanpa dihalangi oleh aparat keamanan TNI dan Polri. Masih banyak luka-luka serius dan ringan yang dialami oleh orang asli Papua. Pertanyaannya, apakah aparat kepolisian Indonesia sudah menangkap para pelaku kriminal ini? Kalau sudah, kapan ditangkap? Siapa-siapa pelakunya pembunuhan? Di mana ditahan para penjahat ini? Dimana proses peradilan dilaksanakan?
Diskriminasi rasial dan ketidakadilan sebagai jantung kejahatan Negara berjalan telanjang dan tergambar jelas dengan penangkapan: Bucthar Tabuni (Deklarator dan Wakil Ketua II ULMWP), Agus Kossay (Ketua Umum KNPB), Steven Itlay (Ketua KNPB Timika), Alex Gobay (Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa USTJ), Fery Gombo (Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa UNCEN), Irwanus Uropmabin (Mahasiswa), Hengky Hilapok (Mahasiswa), dan Basoka Logo (Eksekutif ULMWP).
Rasisme dan ketidakadilan dari penguasa Indonesia juga terbukti dengan diberi kannya kesempatan kepada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk membentuk Partai Politik Lokal dan mengibarkan bendera GAM. Sebaliknya, selama 19 tahun perjalanan pelaksanaan perintah Undang-Undang Negara Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Pemerintah Indonesia menolak semua draft Perdasus tentang Orang Asli Papua, Perdasus tentang Partai Politik Lokal.
Rasisme dan ketidakadilan juga terbukti dalam penerimaan mahasiswa Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). IPDN yang berlokasi di Bumi Perkemahan Waena 99,9% dikuasai oleh orang-orang pendatang. Amanat Undang-Undang Otsus 2001 tentang perlindungan (protection), keberpihakan (affirmative), pemberdayaan (empowering), dan pengakuan hak-hak dasar orang asli Papua (recognition) gagal total.
Rasisme dan ketidakadilan juga terbukti dalam perekrutan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Indonesia. Alasan lama yang digunakan adalah kesehatan dan juga tinggi badan. Kenyataannya, banyak anggota TNI dan Polri yang berbadan tidak tinggi. Pada bulan Maret 2020, ada anggota polisi datang ke kantor Pusat Gereja Baptis West Papua, dan saya pernah menyampaikan kepadanya, “Anda pendek begini anggota polisi?”
Komandan polisi dan anggotanya yang datang dan mendengar itu, mereka berfikir itu hanya bahasa biasa-biasa saja. Tetapi, sesungguhnya itu sindirian keras saya kepada penguasa Indonesia yang berwatak rasis dan tidak adil.
Diskriminasi rasial dan ketidakadilan terbukti dengan dibungkamnya ruang kebebasan berkumpul, kebebasan berbicara di depan umum bagi rakyat dan masyarakat Papua, dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Bahkan pemimpin KNPB, Mako Tabuni tewas ditangan Densus 88 pada 14 Juni 2012 di Perumnas 3 Waena, Jayapura.
Prof. Dr. Richard Chauvel dari Universitas Melbourne pada 6 September 2019 dalam diskusi dengan FISIP UGM bertopik Papua dan Kebangsaan mengatakan, “Ungkapan rasisme terhadap orang Papua telah mempersatukan dan memperkuat orang Papua dimana saja dan dalam posisi apa saja. Seluruh rakyat Indonesia bersuara tidak setuju Papua Merdeka lepas dari Indonesia. Tetapi, sikap dan narasi-narasi seperti rasisme di Malang dan Surabaya sudah menunjukkan bahwa orang Papua bukan bagian dari rakyat Indonesia. Dampak negatif jangka panjang sangat membahayakan masa depan Indonesia. Orang Papua mengatakan, ‘Kami bangsa monyet, jangan paksakan kami kibarkan bendera merah putih’. Pendekatan infrastruktur dan pendekatan militer bukan solusi masalah Papua.”
Cypri J.P. & John Djonga dalam buku Paradoks Papua: Pola-pola Ketidakadilan Sosial, Pelanggaran Hak Atas Pembangunan dan Kegagalan Kebijakan Afirmatif, dengan Fokus di Kabupaten Keerom dengan detail merekam kegagalan Otonomi Khusus 2001.
“Otonomi Khusus (Otsus) sebenarnya dapat merintis jalan keluar untuk berbagai persoalan itu. Kebijakan ini dianggap sebagai terobosan baru bagi pembangunan, sekaligus penyelesaian untuk berbagai persoalan di Papua. Namun, implementasinya, yang kini penuh masalah. Akibatnya, sampai kini akar masalah rakyat Papua belum tertangani.” (hal.xi). “…Ketidakadilan terhadap orang Asli Papua sudah parah dan sistematis. …Kebijakan afirmatif juga masih terbatas retorika;…mesin ketidakadilan dan marginalisasi itu terus bekerja menambah penderitaan orang Asli Papua” (2011:hal.xxv).
Gizi Buruk
Pelapor Khusus untuk Hak atas Pangan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hilal Elver, menyebut kasus gizi buruk yang menimpa suku pedalaman Asmat di Papua sebagai insiden tragis. “Saya ingin menarik perhatian Anda semua pada sebuah insiden yang sangat tragis. Dalam beberapa bulan terakhir, 72 anak meninggal di Kabupaten Asmat, 66 anak meninggal akibat campak dan 6 lainnya akibat gizi buruk.” (CNN, Rabu (18/4/2018)
Hal ini merupakan sesuatu yang memalukan bagi sebuah negara yang punya perkembangan ekonomi yang baik dan sumber daya yang melimpah. Di tengah kelimpahan masih ada warganya yang mengalami gizi buruk.
Gizi buruk dan kematian orang asli Papua ini bertolak belakang dengan janji palsu pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan Pepera 1969 Annex 1 yang dilaporkan perwakilan PBB, Dr. Fernando Ortiz Sanz dari Bolivia. Menteri Dalam Negeri RI Amir Machmud pada pelaksanaan Pepera 14 Juli 1969 di Merauke dihadapan peserta Anggota Musyawarah Pepera menyampaikan janji bohong. “…pemerintah Indonesia, berkeinginan dan mampu melindungi untuk kesejahteraan rakyat Irian Barat, oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, tetapi tinggal dengan Indonesia.”
Realitas yang ada tidaklah sesuai dengan janji tersebut. Sepanjang perjalanan 51 tahun sejak 1969 sampai 2020, Otonomi Khusus 2001 yang sangat paradoks dengan kata-kata indah itu berubah menjadi tragedi kemanusiaan dan malapetaka, penderitaan, tetesan air mata, cucuran darah berkepanjangan, dan tulang belulang yang berserakkan. Itu semua dialami rakyat Papua di atas Tanah mereka sendiri.
Orang Papua Tidak Bisa Diukur dengan Uang
Penguasa Indonesia yang rasis selalu melihat orang asli Papua dari nilai uang. Penguasa Indonesia mengatakan dalam Otsus 2001 terdapat banyak uang. Dan penggunaan dana Otsus harus diaudit atau diperiksa. Sikap pemerintah itu tidak terlihat pada kasus-kasus yang terjadi di Papua. Jarang bahkan “nol” penguasa Indonesia secara terbuka mengutuk kekerasan Negara (pelakunya TNI-Polri) terhadap orang Asli Papua dan meminta para pelaku kejahatan kemanusiaan itu ditangkap, diadili, dan dihukum demi rasa keadilan bagi keluarga korban dan juga orang asli Papua.
Penguasa Indonesia yang berwatak rasisme keliru dalam menilai dan melihat orang asli Papua. Orang Asli Papua mampu dan sanggup hidup tanpa uang Otsus dan juga tanpa Indonesia. Karena, sebelum Indonesia menduduki dan menjajah orang asli Papua, bangsa Papua pernah hidup berdaulat di atas tanah leluhurnya. Itu karena OAP adalah pemilik tanah Papua.
*Penulis adalah Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua; Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC); Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC); dan Anggota Baptist World Alliance (BWA).
Tulisan dari Dr. Socratez Yoman tidak mewakili pandangan dari redaksi