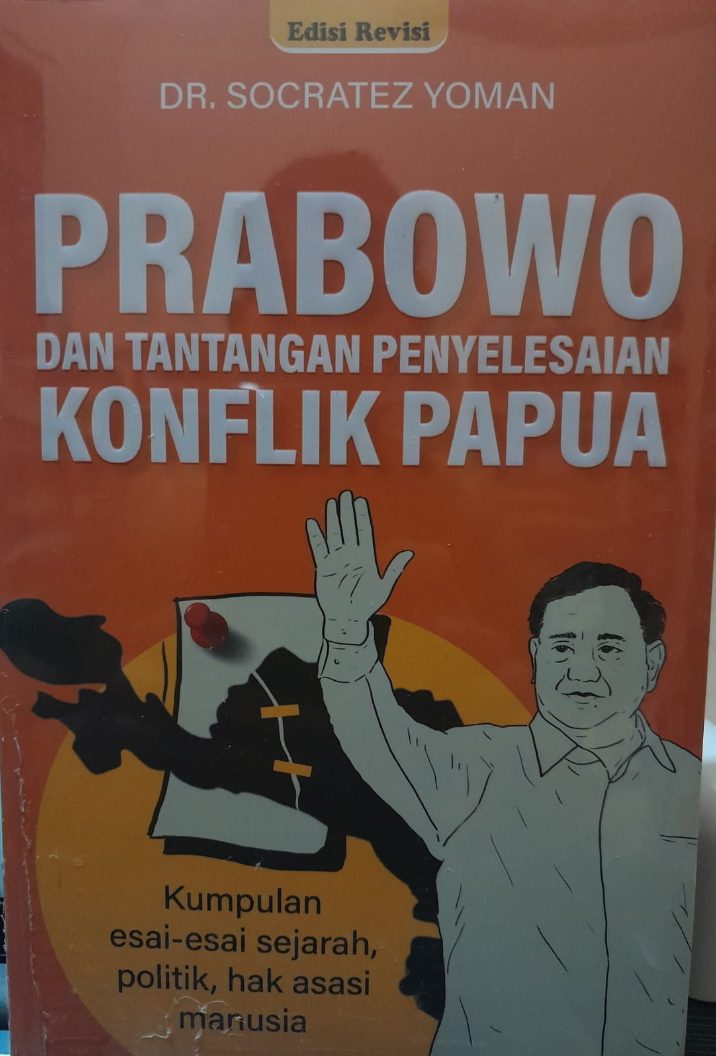Oleh Gembala Dr. A.G. Socratez Yoman
Pada Kamis, 23 Juli 2020 Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pada media. Beberapa kutipan yang bisa dicatat adalah:
“Daripada nanti bunuh orang sana, bunuh orang sini akhirnya, kemudian ya penegakan hukum harus kita lakukan. Bunuh orang, tembak orang, pasti akan ditegakan hukum karena kita negara hukum.”
“Negara tidak boleh kalah dengan siapapun juga, pelanggar hukum, termasuk kelompok bersenjata ini. Kalau dia bunuh orang ya kita tegakkan, kalau kurang pasukan di organic yang ada di daerah (Papua) kurang ya kita tambah.”
Beberapa pernyataan Mendagri Tito Karnavian itu merespon konflik bersenjata yang terjadi di Papua. Dari pernyataan itu, muncul pertanyaan yang mengusik saya dan juga orang-orang asli Papua (OAP), apakah penegakan hukum di Papua hanya berlaku bagi OAP? Dimana rasa keadilan bagi OAP?
Jika merujuk masa-masa konflik yang berlangsung di Papua, ada ribuan OAP yang menjadi korban tewas oleh aparat keamanan. Contoh, peristiwa yang terjadi masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yaitu tewasnya empat siswa di Paniai pada 8 Desember 2014. Peristiwa penembakan ini dilakukan oleh TNI. Apakah para pelakunya juga mendapatkan penegakan hukum yang semestinya, seperti yang diungkapkan Mendagri diatas?
Menurut penulis, ribuan aparat keamanan dan puluhan pasukan khusus yang didatangkan ketanah Papua merupakan cermin dan wajah kekuasaan negara Indonesia yang sesungguhnya, sejak 1963 hingga saat ini.
Ketika saya membuka lembaran sejarah kekuasaan Indonesia di Papua, saya menemukan wajah kekuasaan dan kekerasan telah muncul ditengah orang-orang Papua. Dinamika sejarah dan politik saat itu cukup jelas menggambarkan negara menunjukkan kekuatan dan kekuasaan terhadap orang-orang Papua dengan tidak manusiawi, bahkan tak mengenal penghormatan kepada kemanusiaan.
Saya membaca catatan Acub Zainal dalam buku memoarnya berjudul I Love the Army. Acub Zainal, Panglima Militer Indonesia yang kemudian ditunjuk sebagai Gubernur Irian Jaya saat itu menulis situasi yang menegangkan setelah negara Indonesia mendapatkan kekuasaannya, usai United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) meninggalkan Papua pada 1 Mei 1963.
“Begitu mendapat tempat di Papua setelah UNTEA meninggalkan Papua, para elit yang menampakkan kekuatannya dan membakar semua buku, dokumen-dokumen, jurnal, dan semua tulisan tentang sejarah, etnografi, penduduk, pemerintahan, semua dibakar di depan orang banyak di halaman kantor DPRP sekarang di Jayapura,” tulis Acub Zainal.
Sumber lain dari arsip Partai Nasional Indonesia Daerah Irian Barat yaitu Resolusi Partai Nasional Indonesia (PNI) Daerah Irian Barat, 6 Juni 1963 No.2/PN-II/1963 mengungkapkan adanya kekuatan dan kekuasaan digunakan untuk merampas dan menjarah. Demikian situasi itu digambarkan dalam arsip:
“Pada awal Juni 1963 banyak putra dan putri Irian Barat yang Pegawai Negeri dihentikan dan digeser dan digantikan oleh petinggi Indonesia yang baru datang. Di Jayapura dan Biak perampokan yang dilakukan para pendatang yang masuk ke rumah-rumah pegawai dan menjarah barang-barang berupa pesawat radio, tempat tidur, lemari es, pakaian, bahkan hasil-hasil kebun mereka ambil dan bawa pergi. Ini terjadi di beberapa kota di Papua sejak Mei sampai Juni 1963.”
“Mereka mendatangi rumah-rumah yang baru ditinggalkan petinggi pemerintah Belanda dan kantor-kantor pemerintah, mengambil semua barang-barang dari rumah-rumah dan kantor –kanrtor peninggalan Belanda, kemudian dinaikkan ke mobil/truk yang sudah diparkir untuk dibawa keluar Papua. Setelah merampok barang-barang itu, kloter/rombongan lain masuk lagi ke rumah-rumah para pegawai orang Papua: di Kota Biak, Kota Baru (Jayapura) para elit Indonesia ambil barang-barang dan bawa untuk dikirim keluar Papua. Belakangan Presiden Soekarno sendiri menyampaikan teguran lewat pidato Dewan Pengurus Partai Nasional – Resolusi PNI dalam Rapat Dewan Daerah ke I tanggal 9 Djuni 1963”.
Tak hanya perampasan dan penjarahan, aksi-aksi pembersihan simbol-simbol nasional Papua dilakukan oleh militer saat itu, seperti terungkap dalam Buletin TAPOL No.53 September 1982.
“Pada bulan April 1963, Adolof Henesby Kepala Sekolah salah satu Sekolah Kristen di Jayapura ditangkap oleh pasukan tentara Indonesia. Sekolahnya digerebek dan cari simbol-simbol nasional Papua, bendera-bendera, buku-buku, kartu-kartu, sesuatu yang berhubungan dengan budaya orang-orang Papua diambil. Adolof Henesby dibawa ke asrama tentara Indonesia dan diinterogasi tentang mengapa dia masih memelihara dan menyimpan lambang-lambang Papua.”
Laporan itu juga mengungkapkan aksi ‘bumi hangus’ oleh ABRI terhadap simbol-simbol nasionalisme Papua. “Pembakaran besar-besaran tentang semua buku-buku teks dari sekolah, sejarah dan semua simbol-simbol nasionalisme Papua di Taman Imbi dilakukan ABRI dipimpin oleh Menteri Kebudayaan Indonesia, Mrs. Rusilah Sardjono.
Aksi-aksi ABRI saat itu merupakan bagian dari kebijakan Presiden RI, Ir. Sukarno pada bulan Mei 1963 yang mengeluarkan Surat Larangan No. 8 Tahun 1963 yang isinya “Melarang/menghalangi atas bangkitnya cabang-cabang Partai Baru di Irian Barat. Di daerah Irian Barat dilarang kegiatan politik dalam bentuk rapat umum, demonstrasi-demonstrasi, percetakan, publikasi, pengumuman-pengumuman, penyebaran, perdagangan, atau artikel, pameran umum, gambaran-gambaran atau foto-foto tanpa izin pertama dari Gubernur atau pejabat resmi yang ditunjuk oleh presiden.”
Perampokan dan penjarahan yang dilakukan militer Indonesia digambarkan Djopari sebagai berikut:
“…Belanda waktu berangkat meninggalkan Irian Barat, meninggalkan segala sesuatu yang merupakan sarana umum dan milik pribadi kepada pemerintah setempat serta kenalan atau bawahannya. Dalam hal ini adalah berbagai perlengkapan militer di asrama-asrama militer, perlengkapan di kantor-kantor pemerintah, sarana-sarana di lapangan terbang dan pelabuhan, perlengkapan rumah dinas lengkap dan rumah-rumah pribadi lengkap. Setelah tanggal 1 Mei 1963 masyarakat di kota-kota Jayapura, Biak, Manokwari, dan Sorong menyaksikan berbagai fasilitas untuk digunakan di Irian Jaya itu diangkut ke daerah Indonesia lain menggunakan transportasi yang ada pada waktu itu seperti tempat tidur, kasur, mesin cuci, kaca nako, wash tafel, oven, sepeda, vespa, kipas angina, tengga pesawat terbang di lapangan terbang internasional Mokmer Biak, dan dok apung di Manokwari.” (Djopari, 1993:83, baca: Yoman, Pintu Menuju Papua Merdeka, 2001:49).
Filep Karma dalam bukunya “Seakan Kitorang Setengah Binatang” mengungkapkan bahwa perilaku negara yang memperlakukan orang Papua setengah binatang. “Mereka (baca: Indonesia) memandang, menganggap, dan memperlakukan orang Papua sebagai setengah manusia, tidak diakui sebagai manusia pada umumnya.”
Ia mengungkapkan bahwa perampasan hak-hak orang Papua terjadi diberbagai sektor, baik swasta maupun di pemerintahan. “Contoh, dulu di Papua, ada perusahaan Nieuwnhuijs, yang dimiliki keluarga saya, Rampaisum itu diambil alih oleh orang asal Manado. Sekarang perusahaan itu milik mereka, bergerak dalam ekspedisi muatan kapal laut.”
Negara menggunakan aparat keamanan, termasuk puluhan pasukan khusus yang didatangkan ke Papua, untuk mendidik dang mengubah paradigma atau cara pandang orang Indonesia terhadap OAP. Pendekatan kekuasaan dan keamanan seringkali justru merendahkan martabat orang Papua, yang sesungguhnya membutuhkan penghargaan nilai-nilai kemanusiaan dan merindukan kehidupan yang damai.
Pastor Frans Lieshout, dalam buku Pastor Frans Lieshout OFM: Gembala dan Guru Bagi Papua (2020:593), memberikan kesaksian:
“Pada tanggal 1 Mei 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang telah diutus merupakan kelompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipungut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar demikian.”
Hal yang berbeda diungkapkan oleh Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno dalam buku “Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual” (2015:255-257). Pada bagian bahasan soal Papua, Romo Magnis menulis demikian:
“Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia. Kita teringat pembunuhan keji terhadap Theys Eluay dalam mobil yang ditawarkan kepadanya untuk pulang dari sebuah resepsi Kopasus.”
“Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk ditubuh bangsa Indonesia.” (hal. 255)
“…kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam.” (hal. 257)
Pastor Frans Leishout, OFM melayani di Papua selama 56 tahun sejak tiba di Papua pada 18 April 1969 dan kembali ke Belanda pada 28 Oktober 2019. Pastor Frans dalam Surat Kabar Belanda ‘De Volkskrant’ (Koran Rakyat) yang diterbitkan pada 10 Januari 2020 menyampaikan pengalamannya di tanah Papua.
“Saya sempat ikut salah satu penerbangan KLM yang terakhir ke Hollandia, dan pada tanggal 1 Mei 1963 datanglah orang Indonesia. Mereka menimbulkan kesan segerombolan perampok. Tentara yang telah diutus merupakan kelompok yang cukup mengerikan. Seolah-olah di Jakarta mereka begitu saja dipungut dari pinggir jalan. Mungkin benar-benar demikian.”
“Saat itu saya sendiri melihat amukan mereka. Menjarah barang-barang bukan hanya di toko-toko, tetapi juga di rumah-rumah sakit. Macam-macam barang diambil dan dikirim dengan kapal ke Jakarta. Dimana-mana ada kayu api unggun: buku-buku dan dokumen-dokumen arsip Belanda di bakar.” (2020:593).
Pastor Frans menggambarkan tentang siapa sebenarnya Indonesia. Menurutnya, wajah Indonesia dari semula adalah wajah kekuasaan militer. Urain kesaksian dan pengalaman Pastor Frans saya lihat juga hari ini. Rupa Indonesia di tanah Papua adalah wajah militer yang tak lepas dari sejarah kekerasan. Meski aparat keamanan datang ke kampung-kampung dengan buku dan sapaan, itu tak bisa menghapus wajah kekerasan yang melekat dalam alat-alat negara itu.
*Penulis adalah Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP); dan Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC); Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC); dan Anggota Baptist World Alliance (BWA).
Tulisan dari Dr. Socratez Yoman tidak mewakili pandangan dari redaksi