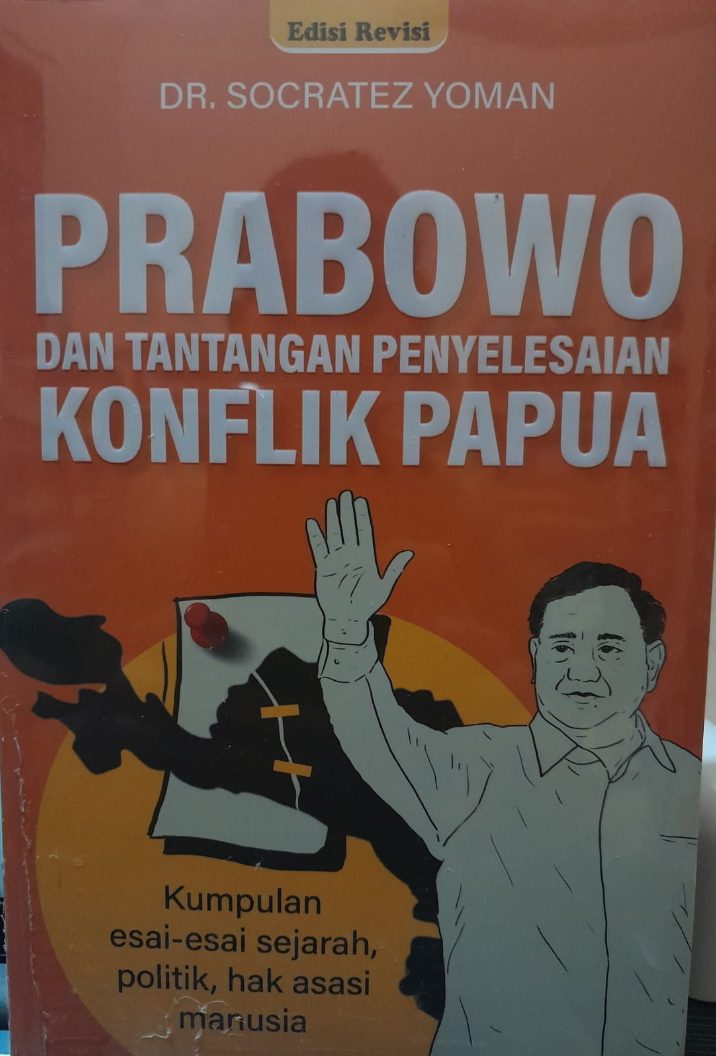Oleh Dr. Socratez Yoman
Rakyat Papua menentang dan menolak hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969. Kenyataan ini terjadi ketika sejarah Pepera 1969 terungkap bahwa pelaksanaannya tidak fair, direkayasa dan intimidatif.
Salah satu kekuatan yang sangat mempengaruhi proses Pepera pada 1969, memilih opsi ikut bergabung dengan pemerintah Indonesia atau berdiri sendiri (merdeka), adalah operasi kekuatan dan mobiliasi yang dilakukan oleh tentara Indonesia, yang saat itu dikenal dengan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Mobilisasi kekuatan militer Indonesia telah ‘memaksa’ orang-orang Papua, yang dipilih sebagai wakil, oleh panitia pemilihan saat itu, untuk memenangkan suara bergabung ke Pemerintah Indonesia. Cara-cara demikian telah menodai prinsip demokratis bagi pelaksanaan Pepera tahun 1969. Bahkan, Pepera dianggap cacat secara hukum internasional.
Bagaimana militer bertindak mempengaruhi proses pelaksanaan Pepera agar para delegasi memilih bergabung dengan Pemerintah Indonesia? Pasca pelaksanaan Pepera 1969, muncul dokumen yang mengungkap peran besar militer dalam memenangkan jajak pendapat itu. Terlihat dalam dokumen militer Surat Telegram Resmi Kol. Inf. Soepomo, Komando Daerah Militer XVII Tjenderawasih Nomor: TR-20/PS/PSAD/196, tertanggal 20-2-1967, berdasarkan Radiogram MEN/PANGAD No: TR 228/1967 TBT tertanggal 7-2-1967, Perihal: menghadapi referendum di IRBA tahun 1969:
“Mempergiatkan segala aktivitas di masing-masing bidang dengan mempergunakan semua kekuatan material dan personil yang organik maupun yang B/P kan baik dari Angkatan Darat maupun dari lain angkatan. Berpegang teguh pada pedoman, referendum di IRBA tahun 1969 harus dimenangkan, harus dimenangkan. Bahan-bahan strategis vital yang ada harus diamankan. Memperkecil kekalahan pasukan kita dengan mengurangi pos-pos yang statis. Surat ini sebagai perintah OPS untuk dilaksanakan. Masing-masing koordinasi sebaik-baiknya. Pangdam 17/PANG OPSADAR”.
Dalam sebuah wawancara dengan penulis di Jayapura pada 11 Desember 2002, Christofelt L. Korua, seorang saksi mata yang merupakan purnawirawan polisi, menyatakan, “Orang-orang Papua yang memberikan suara dalam Pepera 1969 itu ditentukan oleh pejabat Indonesia dan sementara orang-orang yang dipilih itu semua berada di dalam ruangan dan dijaga ketat oleh militer dan polisi Indonesia.” Laporan Resmi PBB, Annex 1, Paragraph 189-200, menyebutkan bahwa kelompok tentara Indonesia dalam jumlah besar hadir pada pemilihan tersebut. Disebutkan kelompok besar tentara hadir dalam Pepera yang dimulai pada 14 Juli 1969 dengan 175 anggota Dewan Musyawarah untuk Merauke.
Carmel Budiardjo, Direktur The Indonesia Human Rights Campaign (TAPOL), pada 26 Maret 2002 menyerukan kepada Sekjen PBB, Kofi Annan, “Dalam bulan Agustus 1969, penguasa Indonesia melaksanakan Pepera di West Niew Guinea (West Irian, kemudian Irian Jaya, dan sekarang Papua) untuk menentukan status masa depan wilayah. Pemilihan menyampaikan delapan dewan bersama 1.025 orang, dilaksanakan di bawah tekanan dari penguasa militer Indonesia.”
Operasi militer juga dilakukan sebelum Pepera digelar beberapa tahun sebelumnya (Raweyai, 2002:33 34). Antara lain, pada masa Kodam dipimpin oleh Brigjen R. Kartidjo (1965 – 23 Maret 1966), dilaksanakan ‘Operasi Sadar’ yang bertugas melakukan kegiatan intelijen, menyadarkan para kepala suku, dan melakukan penangkapan terhadap para pemimpin OPM (Organisasi Papua Merdeka) serta menangkap orang-orang Papua yang menolak integrasi dengan Indonesia.
Kemudian, ketika Brigjen R. Bintoro ditunjuk sebagai Pangdam (23 Maret 1966-25 Juni 1968), beliau memimpin ‘Operasi Bratayudha’ yang bertujuan untuk menghancurkan aktivitas OPM yang dipimpin Ferry Awom di Manokwari dan menguasai wilayah Papua Barat secara keseluruhan. Pangdam berikutnya, Brigjen Sarwo Edhi Wibowo, memimpin tugas ‘Operasi Sadar’ yang bertujuan menghabisi sisa-sisa OPM, merangkul orang-orang Papua untuk memenangkan Pepera 1969, dan melakukan konsolidasi kekuasaan pemerintah Indonesia di seluruh wilayah.
Dokumen lain yang mengungkap aksi militer dalam pelaksanaan Pepera diungkapkan dalam surat kabar nasional Belanda, NRC Handelsblad pada 4 Maret 2000. Sebuah surat rahasia untuk pengamanan dan pemenangan Pepera di Merauke dikirim oleh Komando Militer Wilayah XVII Tjenderawasih, Kolonel Infantri Soemarto NRP.16716, kepada Komando Militer Resort-172 Merauke tanggal 8 Mei 1969, Nomor: R-24/1969. Surat itu berstatus rahasia, tertulis perihal: Pengamanan Pepera di Merauke. Inti dari isi surat rahasia tersebut untuk pemenangan Pepera, berikut potongan kutipannya.
“Kami harus yakin untuk kemenangan mutlak referendum ini, melaksanakan dengan dua metode biasa dan tidak biasa. Oleh karena itu, saya percaya sebagai Ketua Dewan Musyawarah Daerah dan Muspida akan menyatukan pemahaman dengan tujuan kita untuk menggabungkan Papua dengan Republik Indonesia”.
Sintong Panjaitan, pimpinan Tim Irian Barat Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang tiba di Manokwari pada 6 Januari 1967 dalam operasi teritorial untuk memenangkan PEPERA 1969, dalam bukunya “Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando” memberikan bukti-bukti keterlibatan langsung aparat keamanan Indonesia memenangkan Pepera 1969 dengan istilah Operasi Teritorial, Operasi Tempur, Pembinaan, dan Pembentukan DMP. DMP singkatan dari Dewan Musyawarah Pepera bentukan ABRI (kini TNI). Anggota DMP adalah orang-orang yang dipilih oleh ABRI dan Pemerintah dan diawasi ketat di bawah intimidasi, teror, dan ancaman pembunuhan. Tujuannya untuk menggabungkan Papua Barat secara paksa ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
Dalam buku itu Sintong mengungkapkan sejumlah fakta seperti yang termuat dalam kutipan berikut.
“Di Jayapura Panglima Kodam XVII/Tjenderawasih Brigjen TNI Sarwo Edhie, memikul tanggungjawab sangat besar atas keberhasilan Pepera dalam pelaksanaan Pepera. Sarwo Edhi diangkat sebagai Ketua Proyek Pelaksana Daerah. Tugasnya mengendalikan, mengerahkan, dan melakukan koordinasi seluruh kegiatan aparat pemerintah daerah, sipil dan swasta, serta seluruh unsur ABRI di Irian Barat. Di Jayapura Brigjen Sarwo Edhi kepada penulis mengemukakan, Kalau Pepera gagal, kegagalan itu terletak di pundak saya. Sebaliknya kalau nanti Pepera berhasil, akan banyak pihak yang mengaku bahwa keberhasilan itu hasil jerih payah mereka (2009:1969).”
Sintong juga menyebutkan ABRI melalui Kodam XVII/Tjenderawasih melaksanakan Operasi Wibawa. Operasi ini dilakukan pasukan organik dan didatangkan dari luar Irian Barat. Bahkan, operasi ini dikenal berkekuatan jumbo karena jumlah pasukannya mencapai 5.220 personil. Selain dari ABRI, personil lain yang dilibatkan adalah Kopasget atau Pasukan Gerak Tjepat AURI, dan Karsayudha. Tujuan operasi ini adalah mengamankan Pepera, menghancurkan OPM pimpinan Ferry Awom, dan menumbuhkan kewibawaan pemerintah (2009:169).
Fakta lain yang dicatat oleh Sintong Pandjaitan adalah pelaksanaan operasi tujuh bulan sebelum Pepera yang dilakukan oleh satuan operasi bernama Karsayudha yang dikomandoi oleh Kapten Faisal Tanjung. Operasi ini dibawah perintah Pangdam XVII/Tjenderawasih, tujuannya sama, memenangkan Pepera.
“Prayudha 1 di bawah pimpinan Lettu Saparwadi, AMN angkatan 64, ditempatkan di Kabupaten Sorong. Lettu Kuntara memimpin Prayudha 2 di Kabupaten Biak. Prayudha 4 di bawah pimpinan Lettu Wismoyo Arismunandar ditempatkan di Kabupaten Merauke. Lettu Sintong Panjaitan memimpin Prayudha 3 berkekuatan 26 orang di bawah perintah (B/P) Komandan Korem 171/Manokwari, selaku Komandan Operasi Wibawa 1 di Kabupaten Manokwari. Ia dibantu oleh Sujudi yang berpangkat calon perwira (capa) sebagai wakil komandan.” (2009:169-170).
(Keterangan: Karsayudha pimpinan Kapten Feisal Tanjung disebut Karsayudha Wibawa, karena pada waktu itu Kodam XVII/Tjenderawasih sedang melaksanakan serangkaian operasi dengan sandi Wibawa).
Ada berbagai cara dalam operasi tersebut yang digunakan untuk menggagalkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat Papua saat itu. Seperti di Manokwari, misalnya, operasi dijalankan dengan target para pegawai negeri, pemuda pelajar. Faktor yang penting juga pembinaan penduduk melalui operasi teritorial. Aksi-aksi itu diatur dengan rinci, seperti satuan Prayudha 3, yang menugaskan anggota melakukan pendekatan atau ‘pembinaan’ kepada para calon DMP. Setiap KPS dikendalikan oleh 3 personil Sandiyudha yang dikenal handal dalam tempur (2009:182-183).
Pada 30 Maret 1969 Sintong didampingi oleh Sertu Salam menghadiri rapat pembentukan DMP Persiapan yang dipimpin oleh S.D. Kawab, Bupati Manokwari, di kantor kabupaten. Rapat membicarakan pembentukan DMP Manokwari yang akan diputuskan berdasarkan konsultasi dengan Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Soedjarwo Tjondronegoro, SH dari Departemen Luar Negeri RI. Sebelum rapat dimulai, para anggota DPRD yang akan berbicara dalam rapat telah melakukan latihan sebanyak empat kali, dengan disaksikan oleh anggota Prayudha 3 sebagai Pembina. Rapat tetap menolak dilaksanakannya kebebasan memilih secara one man one vote. Kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Pembentukan DMP yang kemudian disingkat menjadi Panitia 9 dengan ketua S.D. Kawab. Prayudha 3 mendapat tugas membantu Panitia 9 untuk bertindak sebagai pengaman dan penghubung antara para pembina di daerah-daerah dengan Panitia 9. Disebabkan kerja Panitia 9 kurang lancar hingga Prayudha 3 yang melakukan pekerjaan itu. Hasilnya diserahkan kepada Panitia 9 (2009:183-184).
Para anggota DMP dikumpulkan di kota Manokwari dengan disertai dua orang pembina, masing-masing Letda Renwaren, seorang Perwira Rohani Katolik, dan serta Abdul Hamid (2009:184). Dalam pelaksanaan Pepera di kabupaten Manokwari, Sintong bertindak sebagai koordinator intelijen dan mengawasi anggota DMP bernama Rumajom yang diperkirakan akan melakukan tindakan negatif. Capa Suyudi, Wadan Prayudha 3 bertindak sebagai Komandan Sektor A di dalam ruang sidang, sedangkan Letda Monthe sebagai Komandan Sektor B. Sementara itu Prayudha 3 mendapat tugas mengerahkan massa sebanyak 5.000 orang untuk menghadiri sidang. Sersan Kepala Simon dibantu oleh tiga orang bertugas mengerakkan massa dari daerah pedalaman dan Sertu Wagimin beserta tiga orang lainnya menggerakkan masa dari daerah pantai. Pengerahan massa menjadi tanggungjawab Prayudha 3 mulai dari pengangkutan sampai ke tempat sidang (2009:185).
Keberhasilan menjalankan peran yang sangat besar dalam menyukseskan Pepera adalah puncak keberhasilan Prayudha 3. Letjen TNI (Purn) Sintong Panjaitan mengakui, “Seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi-operasi Tempur, Teritorial dan Wibawa sebelum dan paska pelaksanaan PEPERA dari Tahun 1965-1969, maka saya yakin PEPERA 1969 di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Pro Papua Merdeka.”
Sintong Panjaitan (2009:185) mengakui perlawanan dari pemuda dan mahasiswa. Pada 19 Juni 1969, 30 orang pelajar yang akan melakukan demonstrasi ditangkap, dari tingkat pimpinan sampai tingkat bawah. Pimpinan mereka seorang mahasiswa Universitas Tjenderawasih. Dalam sidang terjadi demonstrasi kecil, yaitu 17 anak sekolah yang membuat kegaduhan, yang kemudian mereka ditangkap dan dibawa ke Posko Prayudha 3.
Pepera: Tidak One Man One Vote
Referendum untuk rakyat Papua, atau dikenal saat itu dengan Pepera dilaksanakan tidak demokratis dan sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional, yaitu satu orang satu suara atau one man one vote. Saat pelaksanaan Pepera pada 14 Juli-2 Agustus 1969 penduduk Papua yang berjumlah 809.337 jiwa tidak semua dilibatkan untuk memilih dan memutuskan ikut Pemerintah Republik Indonesia atau tidak. Saat itu sekitar 1.025 orang yang dipilih secara tidak demokratis, tidak cukup mewakili rakyat Papua, bahkan mereka tak mendapatkan kebebasan untuk memilih sesuai dengan hati nuraninya.
Pemerintah Indonesia sengaja membentuk badan yang sesuai dengan ‘selera’ atau budaya yang ditanamkan dalam pengambilan keputusan ‘musyawarah untuk mufakat’. Maka, Pemerintah Indonesia membentuk Dewan Musyawarah Papua atau DMP, yang mengatur bagaimana segala sesuatunya berada di bawah kendali Negara Indonesia.
Semakin tidak masuk akal jika kita melihat representasi dari jumlah penduduk Papua yang memiliki hak untuk memilih. Logikanya dari total penduduk OAP 809.337 yang ditunjuk ABRI 1.025 berarti OAP yang tidak ikut terlibat memilih dan menyetujui pernyataan yang disiapkan ABRI sebanyak 808.312 orang. Jumlah wakil yang terpilih itu tidaklah mencerminkan suara orang Papua karena jumlahnya jauh dari setengah jumlah penduduk. Sesuatu yang miris memang.
Tokoh intelektual Papua Agus Alue Alua dalam buku Papua Barat Dari Pangkuan Ke Pangkuan (2000:76), menguraikan data komposisi perwakilan orang-orang Papua yang menjadi peserta utusan dalam Pepera 1969 di berbagai wilayah di Papua.
Pada 14 Juli 1969 di Merauke hanya 175 orang yang dipilih ABRI dan 144.171 jiwa tidak terlibat dalam proses Pepera itu. Apakah 175 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 144.171 orang Merauke untuk memilih Indonesia? Jawabannya adalah tidak. 175 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Merauke.
Kemudian pada 16 Juli 1969 di Jayawijaya hanya 175 orang yang dipilih ABRI dan 165.000 jiwa tidak terlibat dalam Pepera itu. Apakah 175 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 165.000 orang Jayawijaya untuk memilih Indonesia? Jawabannya juga tidak. 175 orang itu dipilih oleh ABRI, bukan utusan rakyat Jayawijaya.
Lalu pada 19 Juli 1969 di Paniai hanya 175 orang dan 156.000 jiwa belum terlibat dalam Pepera. Apakah 175 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 156.000 orang Paniai untuk memilih Indonesia? Jawabannya tidak juga. 175 orang itu dipilih oleh ABRI, bukan utusan rakyat Paniai.
Selanjutnya, 23 Juli 1969 di Fak-Fak hanya 75 orang dan 43.187 jiwa belum terlibat dalam Pepera. Apakah 75 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 43.287 orang Fak-Fak untuk memilih Indonesia? Jawabannya adalah tidak. 75 orang itu dipilih oleh ABRI, bukan utusan rakyat Fak-Fak.
Pada 26 Juli 1969 di Sorong hanya 110 orang dan 75.474 jiwa belum terlibat dalam Pepera. Apakah 110 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 75.474 orang Sorong untuk memilih Indonesia? Jawabannya juga tidak. 110 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Sorong.
Lalu 29 Juli 1969 di Manokwari hanya 75 orang dan 49.875 jiwa tidak terlibat dalam Pepera. Apakah 75 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 49.875 orang Manokwari untuk memilih Indonesia? Jawabannya juga sama, tidak. 75 orang itu dipilih oleh ABRI, bukan utusan rakyat Manokwari.
31 Juli 1969 di Teluk Cenderawasih hanya 130 orang dan 83.000 jiwa tidak terlibat dalam Pepera 1969. Apakah 130 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 83.000 orang Teluk Cenderawasih untuk memilih Indonesia? Jawabannya adalah tidak. 175 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Teluk Cenderawasih.
Terakhir, 2 Agustus 1969 di Jayapura hanya 110 orang dan 81.246 jiwa tidak terlibat dalam Pepera. Apakah 110 orang ini mendapat mandat atau kuasa dari 81.246 orang Jayapura untuk memilih Indonesia? Jawabannya adalah tidak. 110 orang itu dipilih oleh ABRI bukan utusan rakyat Jayapura.
Pelaksanaan Pepera 1969 terbukti bahwa ABRI-lah yang memenangkan Pepera 1969, bukan Orang Asli Papua. Karena penduduk OAP pada tahun 1969 berjumlah 809.337 jiwa dan hanya 1.025 orang yang dipilih ABRI dan 808.312 tidak pernah ikut terlibat dalam Pepera 1969.
Persoalan mendasar yang bisa dilihat dari proses dan hasil Pepera itu ialah tidak ada legitimasi hukum dan dukungan dari mayoritas rakyat dan bangsa Papua kepada Indonesia untuk berada di Papua. Namun, hasil pilihan dari 1.025 orang itu dianggap telah sah karena sudah diakomodir dalam resolusi PBB 2504 tentang hasil Pepera. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, hasil Pepera 1969 terus digugat oleh rakyat Papua, yang diwakili oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), atas dukungan dari negara Vanuatu yang menggugat kembali Indonesia karena ada masalah hukum yang serius dalam pelaksanaan Pepera 1969.
Pelaksanaan Pepera 1969 dinilai punya cacat moral dan hukum serta manipulatif karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Perjanjian New York 15 Agustus 1962 “one man one vote”. Pepera sama sekali tidak menganut hukum itu melainkan dengan cara dan budaya politik Indonesia dengan ‘musyawarah” untuk mencapai mufakat.
Sesudah Manipulasi Pepera Terungkap
J.P. Drooglever menemukan dalam penelitiannya yang berjudul “Laporan Akhir Sekjen PBB Seluruhnya Didasarkan pada Laporan Ortiz Sanz tentang Peranannya dalam Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Bebas.” Laporan ini hanya berisi kritik yang lemah terhadap oposisi dari pihak Indonesia. Atas dasar ini, U. Thant tidak bisa berbuat lain kecuali menyimpulkan bahwa suatu kegiatan pemilihan bebas telah dilaksanakan. Ia tidak bisa menggunakan kata depan yang tegas (the), karena nilai nilai proses itu jauh di bawah standar yang diatur dalam Persetujuan New York. Walaupun dapat ditafsirkan sebagai suatu penilaian yang mencibir, tetapi beberapa pihak justru mengabaikan pengkalimatan yang tidak jelas dalam persetujuan New York itu.”
Pernyataan tersebut termuat dalam “Tindakan Pilihan Bebas, Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri.” Selanjutnya Drooglever (2010:783) mengungkap, “Menurut pendapat para pengamat Barat dan orang orang Papua yang bersuara mengenai hal ini, tindakan Pilihan Bebas berakhir dengan kepalsuan, sementara sekelompok pemilih yang berada di bawah tekanan luar biasa tampaknya memilih secara mutlak untuk mendukung Indonesia.”
Berkaitan dengan hal itu, Dr. Hans Meijer, Sejarawan Belanda dalam penelitiannya yang berhubungan dengan hasil Pepera 1969 di Papua Barat menyatakan bahwa, “Pepera 1969 di Papua Barat benar-benar tidak demokratis.”
Dr. John Saltford, Akademisi Inggris yang menyelidiki hasil pelaksanaan Pepera 1969 menyatakan, “Tidak ada kebebasan dan kesempatan dalam perundingan-perundingan atau proses pengambilan keputusan yang melibatkan orang-orang Papua Barat. Jadi, PBB, Belanda, dan Indonesia gagal dan sengaja sejak dalam penandatanganan tidak pernah melibatkan orang orang Papua untuk menentukan nasib sendiri secara jujur.” (United Nations Involment With the Act of Free Self-Determination in West Papua (Indonesia West New Guinea) 1968 to 1969).
Robin Osborn (2000:30) mengungkapkan, “Bahwa penggabungan daerah bekas jajahan Belanda itu ke dalam wilayah Indonesia didasarkan pada premis yang keliru. Yaitu ketika 1.025 orang delegasi yang dipilih pemerintah Indonesia memberikan suara mereka dibawah pengawasan PBB diartikan sebagai aspirasi politik dari seluruh masyarakat Papua Barat. Kini, premis ini diragukan keabsahannya berdasarkan hukum internasional.”
Dr. George Junus Aditjondro (2000:8) mengatakan, “Dari kaca mata yang lebih netral, hal-hal apa saja yang dapat membuat klaim Indonesia atas daerah Papua Barat ini pantas untuk dipertanyakan kembali”. Tentu ini bisa menjadi pertanyaan kebalikan atas beberapa pernyataan di atas.
Pada hari Sabtu, 16 Januari 2010 di studio Metro TV pada acara Kick Andy, dalam menyikapi pelarangan lima buku oleh Kejaksaan Agung, Ikrar Nusa Bhakti menanggapi kementar saya (Socratez) tentang pelaksanaan Pepera 1969 di Papua Barat yang tidak demokratis dan lebih dimenangkan oleh aparat keamanan Indonesia. Ikrar berkomentar, “Memang apa yang dikatakan pak Socratez tentang pelaksanaan Pepera 1969 yang tidak demokratis itu ada benarnya.”
Menarik menyimak pernyataan Pdt. Dr. Phil Karel Erari dalam buku Yubileum dan Pembebasan Menuju Papua Baru (2006:23), “Rakyat Papua merasa bahwa Pepera adalah rekayasa Pemerintah RI, Belanda, Amerika Serikat dan PBB, di mana rakyat Papua tidak dilibatkan sebagai subyek hukum internasional dan pelaksanaannya tidak dilakukan secara demokratis sesuai dengan kebiasaan dan praktik yang berlaku dalam masyarakat internasional.”
Erari menambahkan (2006:182), “Sejarah Integrasi Papua dalam Indonesia adalah suatu sejarah berdarah. Pelanggaran HAM yang diwarnai oleh pembunuhan kilat, penculikan, penghilangan, perkosaan, pembantaian, dan kecurigaan”. Karel Phil Erari dengan tegas mengatakan, “Secara hukum, integrasi Papua dalam NKRI bermasalah.”
Pada bulan Juni 1969, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia mengakui kepada anggota Tim PBB, Ortiz Sanz, secara tertutup (rahasia) bahwa, “95% orang orang Papua mendukung gerakan kemerdekaan Papua.” Pernyataan ini termuat dalam “Summary of Jack W. Lydman’s report 1969”.
Sebuah pengakuan diberikan Pemerintah Inggris melalui juru bicara House of Lord, Symon Barroness pada 13 Desember 2004. Symon Barroness mengatakan bahwa, “Papua dimasukkan dengan paksa ke dalam wilayah Indonesia melalui rekayasa PEPERA 1969 dan akibatnya bagimana keadaan orang Papua sekarang dan kelangsungan hidup masa depan orang-orang Papua.”
Berbagai protes telah disuarakan para anggota parlemen dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya pada pada 17 Februari 2005, Eni F.H. Faleomavaega yang menyurati Pemerintah Amerika. Pada 14 Februari 2008, Eni bersama Donald Payne, Anggota Kongres Amerika, melayangkan surat kepada Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki-Moon yang berbunyi:
“Referendum (Pepera 1969) bagi orang asli Papua itu dengan jelas menunjukkan bahwa tidak pernah dilaksanakan. Faktanya, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) Anggota Kongres Amerika telah menulis surat, pada tahun 2006, kepada Tuan Annan meminta bahwa PBB tinjau kembali untuk melaksanakan pemerimaan “Pepera 1969” itu.”
Pada 19 Juli 2002, 34 Anggota Parlemen Uni Eropa menyerukan kepada Komisi dan Parlemen Uni Eropa untuk mendesak Sekjen PBB, Kofi Annan, mempertimbangkan kembali penentuan nasib sendiri Papua. Hal itu tertuang dalam laporan Komisi Uni Eropa, “The EC Conflict Prevention Assessment Mission: Indonesia, March, 2002, on unrest in West Papua.”
Pada 31 Januari 1996, sebelum aksi 34 anggota Parlemen Uni Eropa, Parlemen Irlandia mengeluarkan resolusi tentang West Papua yang menyebut ketidak ju juran pelaksanaan Pepera 1969. Aksi ini merupakan sikap tegas negara Irlandia yang menentang hasil keputusan Pepera tahun 1969.
Pada 1 Desember 2008, di gedung Parlemen Inggris, London, Hon. Andrew Smith, MP, dan The Rt. Revd. Lord Harries of Pentregarth dan 50 anggota parlemen dari berbagai negara menyatakan: “Kami yang bertanda tangan di bawah ini dengan jujur dan benar mengakui penduduk asli Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri (self-determination), karena masa depan mereka dihancurkan melalui Pepera 1969.”
Pada 1 Desember 2009 di Gedung Parlemen Inggris, London, para ahli hukum internasional untuk Papua Barat, International Lawyers for West Papua (ILWP) pada saat peluncuran buku Prof. Pieter Drooglever, menyatakan bahwa Pepera 1969 adalah skandal aneksasi illegal.
*Penulis adalah Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP); Anggota Dewan Gereja Papua (WPCC); Anggota Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC); dan Anggota Baptist World Alliance (BWA).
Tulisan dari Dr. Socratez Yoman tidak mewakili pandangan dari redaksi